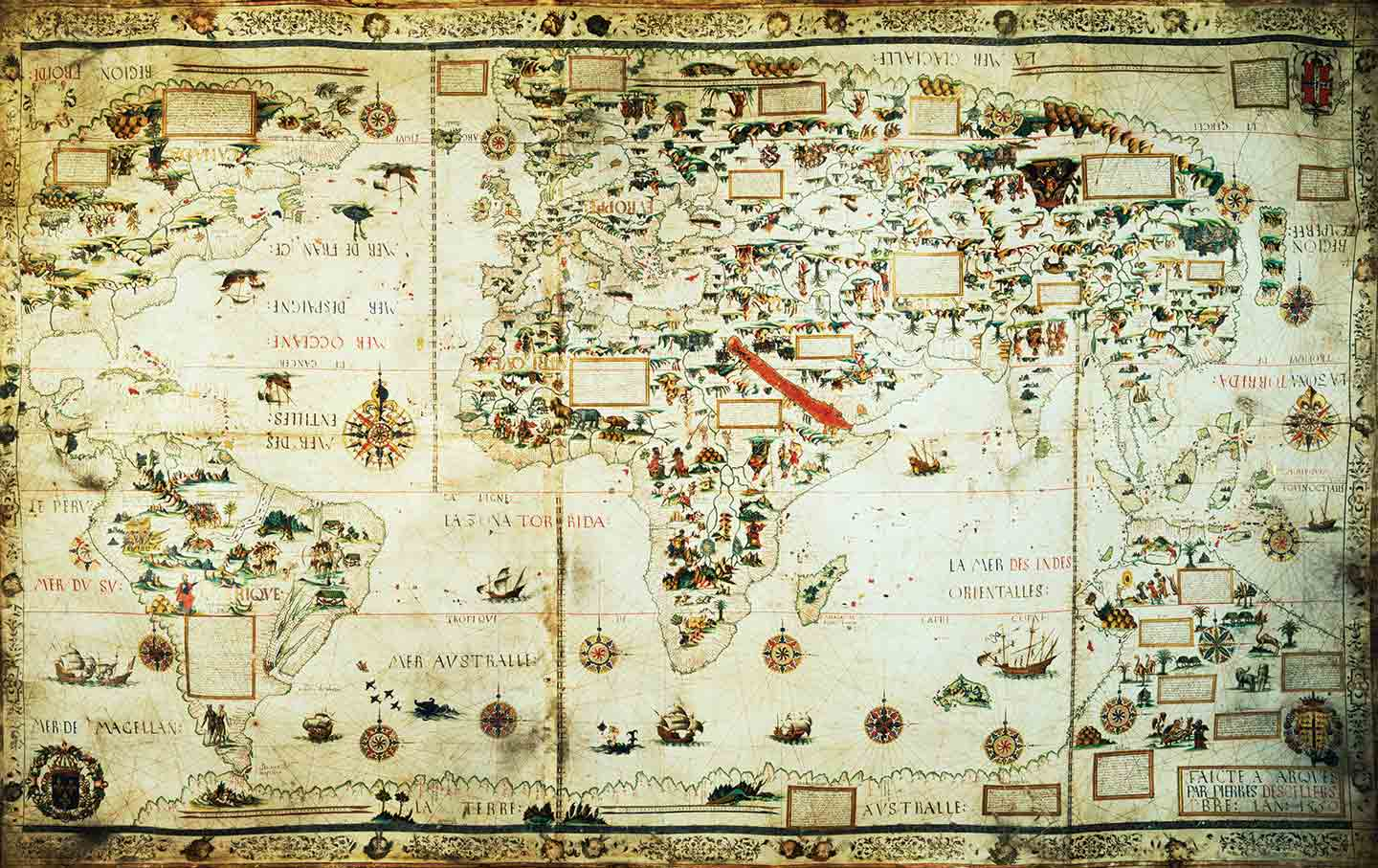Sejak kemunculannya pada pertengahan tahun 1980-an, isu indigenisasi ilmu-ilmu sosial telah menyita perhatian publik akademis Indonesia. Isu ini pun kalau tidak keliru lebih disebabkan oleh sejumlah kecil cendekiawan yang amat dipengaruhi semangat zamannya dalam mencari jati diri keilmuan. Mereka kurang lebih beranggapan bahwa sama seperti hasil kerajinan akal yang lain, ilmu pun bisa digali dari basis lokal. Yang disebut terakhir ini diartikan dengan sistem nilai dan sistem pengetahuan lokal yang masih berlaku dan dapat diandalkan menjadi alternatif paradigma ilmu sosial yang lebih kontekstual. Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya isu indigenisasi lebih merupakan persoalan yang memicu pro dan kontra di kalangan ilmuwan sosial daripada berlaku sebagai pangkal pijak perumusan suatu aliran pemikiran sosial berbasis lokal.
Hal lain yang perlu dikatakan di sini ialah bahwa dalam pewacanaan indigenisasi ilmu-ilmu sosial tersebut hampir tidak terdapat perbedaan yang tegas di antara indigenisasi sebaga bagian dari genealogi pengetahuan berbasis lokal yang hendak diilmiahkan dan indigenisasi sebagai bagian dari kontekstualisasi ilmu-ilmu sosial yang berkembang saat itu dalam berhadapan dengan material dan semantik lokal. Kalau pengertian pertama yang dijadikan landasan berpikirnya, maka indigenisasi akan tampil sebagai sebuah proyek politik, suatu resistensi lokal terhadap sentrum paradigma ilmu-ilmu sosial modern yang dinilai sangat totalitarian. Di dalamnya bekerja sebuah anggapan bahwa ilmu-ilmu sosial modern seluruhnya berasal dari Barat yang tidak memberi ruang sedikit pun kepada model-model pemahaman lain. Barat itu sama dengan anti-perbedaan dan karenanya harus dilawan dengan cara membangun sebuah model pengetahuan lokal yang lebih obyektif dan seterusnya.
Sementara dengan kontekstualisasi kurang lebih dimaksudkan bahwa ilmu-ilmu sosial modern tidak seluruhnya ditolak, melainkan dicoba didapatkan relevansinya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Dari pengertian ini bisa ditangkap suatu penalaran sederhana bahwa persoalan yang melekat pada rezim ilmu-ilmu sosial bukanlah bersifat epistemologis tentang bagaimana suatu pengetahuan terbentuk dan beroperasi sebagai sebuah cara berpikir kolektif. Kontekstualisasi ilmu semata-mata menyiratkan persoalan ilmiah yang metodologis sifatnya. Barangkali juga karena yang umum berlaku adalah penalaran semacam ini maka dalam beberapa tahun terakhir komunitas ilmu sosial di Indonesia amatlah antusias menyambut dan kemudian menereapkan model apropriasi fakta yang dikembangkan ilmuwan sosial seperti Jurgen Habermas dengan pendekatan partisipatorisnya. Tugas ilmu sosial kemudian disederhanakan sebagai misi pencerahan dan emansipasi manusia dari kungkungan ketidaksadaran sistematis dalam mana ilmuwan sosial dituntut lebih dekat dengan subyek atau obyek penelitiannya.
Bertolak dari dua estimasi di atas, baik genealogi maupun kontekstualisasi sama-sama terjebak dalam penyederhanaan persoalan keilmuan yang belakangan dibongkar dan dikritik oleh pendekatan dekonstruksi. Genealogi pengetahuan lokal ternyata berpijak pada keyakinan bahwa lokalitas pengetahuan itu masih mungkin dihidupkan kembali di tengah campur-baurnya berbagai pengaruh dalam kesadaran dan cara berpikir masyarakat lokal. Demikian halnya dengan kontekstualisasi yang memahami distansi atau jarak antara ilmu sosial dan masyarakat sebagai persoalan teknis semata. Dengan perkataan lain, baik radikalisme genealogi maupun revisionisme kontekstualisasi tidak bergerak lebih jauh dari sekedar merayakan perbedaan dengan cara masing-masing. Tidak ada pelampuan yang dramatis dalam dua penalaran ini karena pada dasarnya kedua mainstream yang kabur ini terkungkung dalam ekstrim masing-masing.
Penyederhanaan atau simplifikasi terhadap masalah keilmuan ada baiknya dibaca sebagai sebuah bentuk kegagalan dalam memahami dualisme semantik dan politik representasi yang menjadi karakteristik internal dari cara berpikir ilmiah. Untuk itu bisa dibuat beberapa prasyarat penting sebagai pedoman dalam tahapan-tahapan kritik terhadap cara kerja teori dan metodologi ilmu-ilmu sosial yang konvensional. Pertama adalah bahwa totalitas operasi ilmu-ilmu sosial berlangsung dalam suatu diskursus bahasa yang khas, yakni bahasa ilmiah. Meski tidak jauh beda dari model-model kebahasaan yang lain, bahasa ilmiah itu selalu bekerja dengan prinsip penjarakan (distanction) agar bisa berlangsung proses interpretasi dan pemaknaan atas kenyataan. Prinsip penjarakan ini tidak lagi semata-mata untuk menjaga netralitas sang peneliti atau ilmuwan sosial tetapi lebih daripada itu untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru atas fakta yang nilainya lebih obyektif. Ilmuwan sosial dianggap jauh lebih memahami persoalan masyarakat daripada masyarakat itu sendiri karena yang pertama memiliki model pemahaman dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Bahasa ilmiah serta merta memuat suatu model penalaran yang benar pada dirinya sendiri. Dalam teori-teori sosial seseorang diajarkan untuk percaya kepada representasi. Dengan representasi dimaksudkan bahwa melalui proses proses interpretasi, penelitian dan teoretisasi, fakta ‘asli’ dihadirkan kembali dalam bentuk yang lebih sistematis, dilihat kaitannya dengan hal-hal lain. Hanya saja fakta tersebut yang kemudian menjadi fakta ‘ilmiah’ diterima begitu saja karena ada kepercayaan bahwa metodologi ilmiah merupakan cara terbaik mengapropriasi kenyataan. Mengapa bisa terjadi demikian? Salah satu jawaban yang mungkin adalah adanya keyakinan kolektif di kalangan ilmuwan bahwa bahasa ilmiah atau proses interpretasi itu bersifat netral. Dalam hal ini mudah terlihat bagaimana bahasa diperlakukan semata-mata sebagai instrumen yang siap pakai.
Kedua, selain instrumentalisasi terhadap bahasa ilmiah, ilmu-ilmu sosial hanya mungkin terus ada sepanjang masih terpelihara konsensus di kalangan ilmuwan tentang universalitas dan obyektivitas paradigma ilmu-ilmu sosial modern. Konsensus ini lebih bersifat tidak sadar atau tepatnya, sebagai hasil dari suatu habitus komunitas akademis yang berlangsung dalam satu atau lebih periode dan kemudian menjadi tradisi dengan bangunan institusional yang kokoh. Tanpa konsensus mustahil ada praktik-praktik keilmuan yang dikenal sampai saat ini. Begitu pula ilmu-ilmu sosial di Indonesia memiliki sejarahnya sendiri yang tidak terlepas dari perkembangan sosial dan politik dalam masyarakat yang lebih luas. Sejarah dan tradisi biasanya sangat mempengaruhi kuat atau lemahnya konsensus tersebut.
Dalam kasus ilmu-ilmu sosial di Indonesia, tidaklah butuh riset yang berlarut-larut untuk mengatakan bahwa konsensus di kalangan ilmuwan sosial Indonesia terlihat amat kuat bukan karena akibat dari berlakunya satu atau lebih paradigma sebagaimana dikemukakan Thomas Kuhn dalam maha karyanya, Structure of Scientific Revolution, tetapi lebih disebabkan oleh kedekatan ilmu-ilmu sosial dengan perkembangan sosial dan politik sebagaimana kalau kita meminjam model analisis wacana Foucault dalam maha karyanya, Archeology of Knowledge. Ini barangkali menjadi sebab mencuatnya isu indigenisasi sejak dua dekade silam ketika tidak sedikit ilmuwan sosial Indonesia ingin mengukuhkan identitas ke-indonesia-an dalam perspektif dan penelitian mereka.
Dua karakteristik di atas, bahasa ilmiah dan konsensus, ternyata menjadi alasan utama mengapa indigenisasi ala genealogi dan indigenisasi ala kontekstualisasi itu tidak bisa dengan mudah dirumuskan dalam bentuk-bentuknya yang konkrit. Bahkan dalam tulisan ini, penulis hendak menegaskan bahwa isu indigenisasi yang demikian itu tidak saja sulit diwujudkan tetapi juga tidak punya kemungkinan sama sekali karena ia lahir dari sebuah sikap ilmiah yang keliru. Sumber utama dari kekeliruan ini datang dari keterbatasan kita dalam memahami epistemologi ilmu. Dengan epistemologi, ilmu memperoleh tempat khusus dalam kehidupan masyarakat modern. Epistemologi memberi ilmu suatu cara menghasilkan kenyataan, bukan hanya mengolah data yang ‘obyektif’. Setiap kerja interpretasi ilmiah terhadap kenyataan sosial sekaligus berarti proses produksi makna, entah untuk membenarkan teori yang sudah ada atau menentang kebakuan definisi dan konsep dengan membuka medan analisis baru tempat berbagai inovasi semantik berlangsung secara terus-menerus. Dengan kata lain, epistemologi membentangkan suatu horison interpretasi dan pemaknaan yang tidak habis-habisnya. Suatu horison imajinasi yang di-sistematisasi dan di-disiplinkan dengan proposisi dan hipotesis sebagai pijakan menuju pembentukan sebuah teori.
Kalau indigenisasi hendak diartikan sebagai inkarnasi pengetahuan lokal dalam epistemologi ilmu-ilmu sosial modern maka dari kita dituntut untuk menemukan dan merumuskan epistemologi pengetahuan lokal itu sendiri. Pekerjaan ini pun tentu tidak akan membawa hasil apa pun karena pengetahuan tidak ada hubungannya sama sekali dengan teritori. Pengetahuan apa pun bentuk dan isinya tidaklah bersifat spasial tetapi bersifat kreatif, selalu direproduksi sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Pengetahuan masyarakat lokal terus berkembang melampaui batas-batas arkaiknya, berproses dalam suatu dialektika yang tak pernah tuntas. Justru dalam berhadapan dengan dinamika de-teritorialisasi pengetahuan lokal yang selalu fluktuatif ini, ilmu-ilmu sosial modern cenderung bersikap positivistik dalam memahami kecenderungan-kecenderungan dalam masyarakat. Hanya dengan cara demikian, barulah ilmu-ilmu sosial dapat menunjukkan jati dirinya ekslusif melalui definisi, konsep, dan teori. Jarak yang sengaja dibuat agar ilmu bebas dari bias kepentingan malah kembali merefleksikan ketidakmungkinannya menjadi model representasi kenyataan.
Perlulah selalu diingat bahwa pengetahuan sosial yang dibakukan secara ilmiah selalu merupakan hasil observasi dan interpretasi. Ia bukanlah penggalan kenyataan melainkan gambaran tentang kenyataan. Kalau pun ada sementara ilmuwan mengklaim bahwa pengetahuan lokal itu masih berkembang dan perlu dibela dengan menjadikannya suatu diskursus ilmiah, maka ilmuwan tersebut sudah pasti mengabaikan kenyataan bahwa pengetahuan lokal adalah juga hasil interpretasi. Begitu pula halnya dengan adanya anggapan bahwa indigenisasi ilmu-ilmu sosial bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kapasitas intelektual organik, yakni mereka yang lahir dan berkembang di dalam suatu lokalitas budaya tertentu. Hanya saja dalam kenyataannya intelektual organik tidak juga luput dari dialektika pengetahuan sosial dalam masyarakatnya. Malah bisa jadi mereka adalah korban pertama dari sinkretisasi berbagai jenis pengetahuan yang berlangsung tumpang tindih dalam diskursus pengetahuan masyarakat post-kolonial.
Meskipun demikian, semangat di balik isu indigenisasi ini tidak bisa diindahkan begitu saja. Pelajaran penting yang bisa dipetik adalah bahwa masyarakat memerlukan pedoman dalam berhadapan dengan perubahan yang pesat saat ini. Pedoman tersebut sangat diharapkan dapat disediakan oleh ilmu-ilmu sosial modern. Itupun tidak harus ditunjukkan melalui serangkaian riset ‘partisipatoris’ atau juga tidak harus dalam bentuk advokasi besar-besaran yang didanai oleh kepentingan korporasi-korporasi global yang berkedol filantropis. Bagaimana pun juga, university-industrial complex bukanlah jalan keluar yang diharapkan. Malah tukar-menukar kepentingan di antara dua yang sangat kontras ini semakin melanggengkan perlakuan ilmiah terhadap masyarakat sebagai obyek pengamatan dan pengawasan (object of surveillance) dan kelinci percobaan. Tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk menyaksikan tidak adanya manfaat dari proyek ‘pemberdayaan’ dengan model klinis dari kerjasama tersebut.
Salah satu mekanisme yang barangkali bisa menolong ilmu-ilmus sosial dalam upaya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adalah dengan mentransformasikan epistemologinya supaya lebih terbuka dan kaya dengan berbagai pendekatan. Menyitir perkataan Richard Rorty dalam Philosophy and Mirror of Nature yang termashyur itu, ilmu-ilmu sosial tidak lagi menjadi bagian dari universitas, melainkan bagian integral dari societas. Kalau dengan konsep universitas ilmu-ilmu sosial sangat berambisi menemukan kebenaran ilmiah, maka dengan konsep societas ilmu-ilmu sosial menjadi medan diskursif yang kaya dengan berbagai narasi pengetahuan. Positivisme ilmu mengakibatkan pembatasan terhadap pengetahuan (restriction of meaning), sedangkan diskursivitas ilmu-ilmu sosial memungkinkan adanya perbedaan narasi dan keberlimpahan makna (surplus of meaning).
Di sinilah tantangan komunitas ilmuwan sosial, bagaimana mengondisikan epistemologi ilmu agar tidak lagi kebal terhadap kritik dan dengan ikhlas memberi tempat yang seluas-luasnya kepada model-model pembentukan pengetahuan yang berbeda di dalam diskursus keilmuannya. Bagaimana agar interpretasi ilmiah itu tidak mutlak berkiblat pada universal-pragmatics yang hendak dijadikan oleh Teori Kritis sebagai fundamen satu-satunya bagi proyek penuntasan modernitas yang belum selesai. Kalau sebuah teori tetap dirumuskan atau dibenarkan dengan berpegang pada klaim obyektivitas dan universalitas maka misi emansipasinya pun tidak bisa dipertahankan lagi. Keterbukaan epistemologi mengandaikan bahwa semua jenis pengetahuan punya kesempatan yang berimbang dalam penghadirannya di dalam diskursus ilmu-ilmu sosial. Tabel nilai logosentrisme Barat yang diam-diam menjadi leitmotif reproduksi kebenaran ilmiah haruslah terlebih dahulu ditinggalkan karena hanya dengan cara demikian barulah epistemologi ilmu berubah bentuknya menjadi medan diskursif.
Dalam arti itu, kita tidak perlu berbusa-busa membicarakan indigenisasi. Dalam medan diskursif, satu atau lebih persepktif baru akan muncul dan barangkali lebih bisa dijadikan pegangan yang kuat dalam mengkaji kenyataan sosial. Peralihan dari epistemologi menjadi medan diskursif dengan sendirinya membawa semangat pembebasan dan kreativitas imajinasi sosiologis tanpa harus di-disiplin-kan dengan tabu semantik ilmiah. Dengan sendirinya pula teori-teori metanarasi berhenti sebagai kanon yang harus dijaga mati-matian oleh para penganutnya. Medan diskursif adalah sebuah khasanah, sebuah horison pertemuan berbagai model pengetahuan, ia adalah gambaran ideal dari masyarakat dari masyarakat bebas distorsi itu sendiri. Mengajarkan kebebasan sebagai suatu imperatif pengetahuan sangatlah beresiko menjadi pengontrol kebebasan karena kebebasan bukanlah materi yang dihasilkan oleh tindakan mendidik melainkan sebuah suasana yang selalu lahir dari keadaan ada-bersama perspektif lain.
Hal lain yang tak kalah menariknya ialah bahwa dengan mengandaikan epistemologi sebagai medan diskursif, indigenisasi pun tidak harus dihubungkan dengan orisinalitas pengetahuan lokal. Orisinalitas sesungguhnya bagian dari masalah yang akan selalu muncul kalau ilmuwan sosial masih percaya kepada politik representasi ilmiah. Tidak ada pengetahuan yang benar-benar murni dalam arti bebas dari tubrukan-tubrukan diskursif dalam medan aktualitasnya yang lebih luas. Apa yang kita sebut sebagai pengetahuan selalu merupakan percikan atau katarsis dari suatu proses penemuan antar narasi yang tak berkesudahan. Pengetahuan sosial, apa pun genre dan substansinya, bukanlah produk hasil kerja teknis sekali jadi, tetapi menjelma sebagai basis kreasi bagi sedemikian banyak pengetahuan baru. Dengan demikian pengetahuan itu bersifat reflektif dan prospektif, tidak melulu merujuk kepada masa lalu atau hal-hal yang sudah terbentuk.
Selain daripada itu, revaluasi yang radikal terhadap epistemologi ilmu membuat kita harus memeriksa kembali semangat pencerahan yang sekian lama yang melegitimasi praktik epistemologi tersebut. Pencerahan sebagai sebuah nilai universal sebetulnya menyembunyikan suatu barisan kategori imperatif pengetahuan ilmiah yang sampai saat ini masih berlaku sebagai teknologi produksi makna tunggal tentang kemajuan, perubahan, kebaikan, kebahagiaan dan sejumlah konsep sejenisnya. Semangat pencerahan yang diusung atau dimungkinkan oleh epistemologi ilmu kemudian diketahui sarat dengan kepentingan ideologis, termasuk yang dibesar-besarkan oleh aliran yang mengganggap teori-teorinya bersifat kritis. Karena itu bisa dikatakan bahwa epistemologi semacam ini menunjukkan kontradiksi internal yang membutuhkan revaluasi agar bisa terjadi transformasi dalam diskursus ilmu itu sendiri. Kita pun tahu persis bahwa pencerahan itu tidak harus dijadikan sebuah aturan universal melainkan diterima sebagai semangat keilmuan yang mengondisikan perbedaan-perbedaan perspektif sebagai hasil dari berbagai cara berada dalam dunia makna.
Epistemologi ilmu memang akan selalu melahirkan sederetan metanarasi yang nyaris absolut. Akan tetapi, dalam kenyataannya metanarasi setotal apapun pengaruhnya tidak akan pernah sanggup meniadakan perbedaan, malah politik representasi kebenaran tunggalnya itulah yang pada gilirannya mengondisikan adanya sedemikian banyak lapisan pengetahuan dalam diskursus ilmu-ilmu sosial. Dalam diskursus ilmu positivistik yang totalitarian, lapisan-lapisan pengetahuan lokal-marjinal tidak bisa tereliminas seluruhnya, tetapi sebatas terbenam dalam arsip-arsip pengetahuan kontemporer yang tinggal menunggu momentum aktualisasinya dalam fragmen historis tertentu. Demikianlah hendak ditegaskan pula bahwa indigenisasi pun tidak harus dirumuskan dengan semangat kontestasi politik wacana-wacana minor karena sudah ada semacam asas internal atau revaluasi diri dalam diskursus ilmu itu sendiri. Dengan kata lain, pergolakan menentang metanarasi bukanlah peristiwa yang sengaja diciptakan, melainkan akibat logis dari ‘discontents of scientific discourse’.
Diskursus ilmu-ilmu sosial positivistik mengandaikan bahwa semua jenis pengetahuan sosial memuat cita-cita yang sama. Ini bisa disebut sebagai kalkulus metafisis yang kerjanya hanyalah simplifikasi terhadap perbedaan. Konsep sejarah, misalnya, melihat perubahan sebagai hal yang selalu bergerak secara linear, suatu kontinuum menuju titik pusat tertentu, entah itu puncak peradaban atau sintesis final bagi segala tese dan antitese. Dari konsep ini pun akan terlihat jelas bagaimana perbedaan konsep tentang ruang dan waktu hendak diubah menjadi satu cara pandang yang normal. Normalisasi terhadap keunikan perspektif adalah karakteristik yang amat menonjol dalam diskursus ilmu-ilmu sosial modern, termasuk bidang studi sejarah, antropologi, arkeologi, dan psikologi. Seluruh bidang kajian manusia dan masyarakat ini berkiblat kepada epistemologi renainsans yang sekarang ini tampil sebagai diskursus normal (normal discourse)—suatu diskursus pengetahuan yang dominan di berbagai universitas dan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.
Kembali ke pokok soal yang dibahas dalam tulisan ini, akan segera terbaca bahwa isu indigenisasi tidak banyak manfaatnya kalau diangkat hanya karena adanya kebutuhan akan identitas. Jika memang demikian, maka isu indigenisasi ini lebih tampak sebagai sebuah rekayasa kebudayaan ilmiah ketimbang sebagai suatu tawaran transformasi dalam diskursus normal. Ada baiknya isu ini dianggkat sebagai kritik terhadap ilmu-ilmu sosial agar lebih berlaku sebagai diskursus abnormal (abnormal discourse) yang selalu siap sedia membesarkan perspektif-perspektif lokal-marjinal dalam bidang kajian masing-masing. Hanya dengan cara itu, hubungan antara ilmu dan masyarakat diperbaharui kembali, bukan lagi dengan revisi metodologi supaya menjadi ‘partisipatoris’, melainkan dengan membiarkan pengetahuan-pengetahuan lokal berbicara dalam suatu model dialog tanpa tabu semantik ilmiah. Dalam medan diskursif itulah penjarakan yang menjadi ciri khas representasi teori dan riset ilmiah sepenuhnya diganti dengan percakapan dialogis dan multi-disiplin. Karakter ilmuwan sosial pun ikut berubah dari seorang pakar yang mahir mendemonstrasikan kebenaran ilmiah menjadi seorang cendekiawan yang bekerja keras dalam membuka horison pertemuan berbagai jenis pengetahuan.
Demikianlah tulisan singkat ini hendak menyampaikan bahwa isu indigenisasi dapat menjad awalan dalam proses transformasi ilmu-ilmu sosial dari epistemologi menuju medan diskursif. Perubahan yang dramatis ini meminta banyak pergeseran fundamental dalam cara ilmuwan bersikap dan menafsir kenyataan. Itu pun bisa terjadi apabila ada perubahan radikal dalam model pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Menjadi seorang ilmuwan sosial tidak selalu harus disebabkan oleh pencapaiannya dalam membenarkan atau menentang sebuah teori tertentu, tetapi juga karena kehebatannya dalam merumuskan suatu perspektif baru dan keberaniannya mempelajari alternatif-alternatif pengetahuan lain yang barangkali belum mendapat tempat dalam wacana ilmu-ilmu sosial modern di Indonesia selama ini. Dalam arti ini, ilmuwan sosial selalu menjadi pelopor pemikiran alternatif dengan membuka medan diskursif bagi kreativitas berpikir. Menyitir intisari Grammatology Derrida, seorang ilmuwan sendiri harus terlebih dahulu menghancurkan metanarasi (the end of the book) dan mulai belajar menulis kenyataan dengan cara-cara baru (the beginning of writing).
Majalah Sintesa, Fisipol UGM, 2006
Sumber Bacaan
Noam Chomsky. 1980. Rule and Representation. New York: Colombia University Press
Pierre Bourdieu. 1988. Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press
Jacques Derrida. 1976. Of Grammatology. Baltimore: the John Hopkins University Press
——————–1987. Writing and Difference. Chicago: the University of Chicago Press
Michel Foucault. 1982. The Archeology of Knowledge, and Discourse on Language. New York: Pantheon Books
Jurgen Habermas. 1988. On the Logic of Social Sciences. Cambridge: The MIT Press
Ignas Kleden. 1988. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3S
Thomas Kuhn. 1970. The Structure of Scientific Revolution. Chicago: The University of Chicago Press
Richard Rorty. 1980. Philosophy and Mirror of Nature. New Jersey: Pricenton University Press